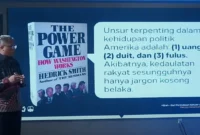Oleh: M. Ismail Yusanto
Digging up the past adalah slogan yang sangat terkenal di kalangan para arkeolog. Ini mewakili semangat mereka untuk mengungkap masa lalu melalui usaha penemuan dan penggalian situs-situs bersejarah. Hasilnya adalah sebuah rekonstruksi kehidupan atau peradaban di masa lalu yang diharap bisa memberi pelajaran kepada kehidupan sekarang dan di masa mendatang.
Tapi slogan itu kiranya tepat juga dipakai oleh kita saat ini yang konsern pada pentingnya pelurusan sejarah. Terlebih setelah Presiden Jokowi – memenuhi janji kampanye saat pilpres tahun lalu – menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri tidak lepas dari kiprah santri dan para kiai dalam melawan penjajah yang ketika itu terus berusaha mengancam kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan.
Pada 21 Oktober 1945, berkumpul para kiai se-Jawa dan Madura di kantor ANO (Ansor Nahdlatul Oelama). Setelah rapat darurat sehari semalam, pada 22 Oktober dideklarasikanlah seruan jihad fi sabilillah yang belakangan dikenal dengan istilah Resolusi Jihad. Intinya, membela kemerdekaan Indonesia sebagai negeri muslim dari kaum penjajah adalah kewajiban syar’iy. Inilah jihad, yang diperintahkan Allah SWT, dan pelakunya sangat dimuliakan.
++++
Kita tentu berharap, penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional bukan sekadar pemenuhan janji bagi kepentingan politik pencitraan, tapi ada misi yang lebih jauh, yakni usaha untuk mengungkap kebenaran sejarah. Misi ini sangat penting karena pelurusan sejarah akan berpengaruh besar dalam ikhtiar membangun kesadaran publik yang benar di masa mendatang.
Kita tahu, sejarah memang tidaklah netral. Sejarah adalah realitas tangan ke dua (second-hand reality) yang sangat tergantung pada siapa yang menuliskan, dan atas dasar kepentingan apa sejarah itu ditulis. Di sinilah, demi memuluskan kepentingan politik penguasa, kejahatan penulisan sejarah kerap terjadi.
Setidaknya ada 3 kejahatan penulisan sejarah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan peran Islam dalam sejarah bangsa dan negara ini.
Pertama, penguburan atau peniadaan peristiwa sejarah.
Salah satu contoh paling nyata, ya soal Resolusi Jihad itu. Bila sejarah pergerakan kemerdekaan ditulis secara jujur, mestinya akan terbaca sangat jelas peran besar para santri yang tergabung dalam Hizbullah dan para kyai yang tergabung dalam Sabilillah dalam periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lebih khusus peran KH Hasyim Asy’ari saat mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 untuk melawan penjajahan Belanda yang ketika itu, dengan membonceng sekutu, hendak kembali bercokol.
Menurut cucu KH Hasyim, KH Salahuddin Wahid, resolusi atau fatwa itu telah mendorong puluhan ribu muslim, utamanya di Surabaya, untuk bertempur melawan Belanda dengan gagah berani. Peristiwa heroik di Hotel Oranye, Surabaya, itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, 10 November. Tanpa resolusi itu, mungkin semangat melawan Belanda dan sekutu tidak terlalu tinggi. Tapi, dalam buku sejarah, peristiwa penting itu tidak ditulis. Sungguh aneh, peristiwa 10 November selalu disebut-sebut, tapi Resolusi Jihad yang membuat peristiwa 10 November bisa terjadi malah disembunyikan.
Buku Resolusi Jihad Paling Syar’iy, yang ditulis oleh Gugun el Guyanie (Pustaka Pesantren, 2010) adalah salah satu buku yang dari sub judulnya “Biarkan kebenaran yang hampir setengah abad dikaburkan catatan sejarah itu terbongkar” menggambarkan semangat untuk mengungkap kebenaran sejarah, khususnya di seputar Resolusi Jihad, yang menurut sejarahwan Belanda Martin van Bruinessen, peristiwa penting ini memang tidak mendapat perhatian yang layak dari para sejarahwan.
Kedua, pengaburan peristiwa sejarah.
Contohnya, siapa sebenarnya inspirator kebangkitan nasional melawan penjajah? Bila sejarah mencatat secara jujur, mestinya bukan Boedi Oetomo, melainkan Syarikat Islam (SI) yang merupakan pengembangan dari Syarikah Dagang Islam (SDI) yang antara lain dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, yang harus disebut sebagai cikal bakal kesadaran nasional melawan penjajah. Sebagai gerakan politik, SI ketika itu benar-benar memang bersifat nasional, ditandai dengan eksistensinya di lebih dari 18 wilayah di Indonesia, dan dengan tujuan yang sangat jelas, yakni melawan penjajah Belanda. Sebaliknya, Boedi Oetomo sesungguhnya hanya perkumpulan kecil, sangat elitis, bahkan rasis, serta sama sekali tidak memiliki spirit perlawanan terhadap Belanda. Tapi mengapa justru sejarah menempatkan Boedi Oetomo sebagai pelopor?
Ketiga, pengaburan konteks peristiwa sejarah.
Tentu bukan sebuah kebetulan belaka ketika Kebangkitan Nasional ditetapkan berdasar pada kelahiran Boedi Oetomo, bukan Sarekat Islam – sebagaimana juga Hari Pendidikan Nasional, bukan didasarkan pada kelahiran Muhammadiyah dengan sekolah pertama yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912, kemana Ki Hadjar waktu itu banyak belajar. Ki Hadjar sendiri baru mendirikan sekolah Taman Siswa pada 1922. Sebab, bila itu dilakukan maka yang akan mengemuka tentu adalah spirit atau semangat Islam. Dalam setting kepentingan politik penguasa saat itu, hal itu sangatlah tidak dikehendaki.
Padahal, spirit Islam sesungguhnya telah lama menjadi dasar perjuangan kemerdekaan di masa lalu. Peperangan yang terjadi pada abad ke-19 melawan Belanda tidak lain didorong oleh semangat jihad melawan penjajah. Ketika Pangeran Diponegoro memanggil sukarelawan, maka kebanyakan yang tergugah adalah para ulama dan santri dari pelosok desa. Begitu juga pemberontakan petani menentang penindasan yang berlangsung terus-menerus sepanjang abad ke-19 selalu dibawah bendera Islam. Perlawanan yang dilakukan oleh Tengku Cik Di Tiro, Teuku Umar dan diteruskan oleh Cut Nyak Dien dari tahun 1873-1906 adalah jihad melawan kape-kape Belanda. Begitu juga dengan perang Padri. Sebutan Padri menggambarkan bahwa perang ini merupakan perang keagamaan. Jadi, jelas sekali ada usaha sistematis untuk meminggirkan, bahkan menghilangkan peran Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan serta menghilangkan spirit Islam dari wajah sejarah bangsa dan negara ini.
Oleh karena itu, penetapan Hari Santri Nasional harus bisa dijadikan momentum untuk melawan kejahatan sejarah itu, serta usaha menulis ulang sejarah: tentang apa yang disebut kebangkitan nasional, pendidikan nasional dan sejarah nasional lainnya, termasuk sejarah pergerakan pra kemerdekaan secara kritis, jujur dan obyektif sehingga peran Islam bisa diletakkan secara tepat. Sejarah dalam istilah al Qur’an sebagaimana kisah, mengandung ibrah atau pelajaran. Pengaburan apalagi penguburan sejarah dari fakta yang sebenarnya tentu akan menutupi ibrah yang mestinya bisa didapat.
Maka, bila mengacu kepada sejarah yang benar tentang peran Syarikat Islam, KH Ahmad Dahlan, dan lannya, juga peran KH Hasyim Asy’ari dengan Resolusi Jihadnya serta peran Hizbullah – Sabilillah, kita tentu akan mendapatkan spirit Islam itu. Juga bahwa Kebangkitan hakiki adalah kembalinya kesadaran akan hakikat hidup manusia sebagai abdullah dan khalifatullah dengan misi untuk menyembah Sang Khaliq dan memakmurkan bumi dengan menjalankan segala titahNya. Jadi, kebangkitan bukan hanya sebuah kata sloganistik, tetapi suatu kata yang menginisiasi perjuangan bagi sebuah perubahan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dari penjajahan ideologi-ideologi jahiliah yang menyengsarakan rakyat menuju yang memberikan rahmat bagi semua. Itulah kebangkitan dengan spirit Islam, yang ketika itu digelorakan oleh Cokroaminoto dan Sarekat Islam. Spirit Islam semacam itulah yang diperlukan sebagai sumber kekuatan perjuangan guna membawa negeri ini ke arah yang lebih baik di bawah ridha Ilahi.
Jadi, Hari Santri Nasional mestinya bukan sekadar digging up the past (mengungkap masa lalu), tapi digging up the truth (mengungkap kebenaran)!