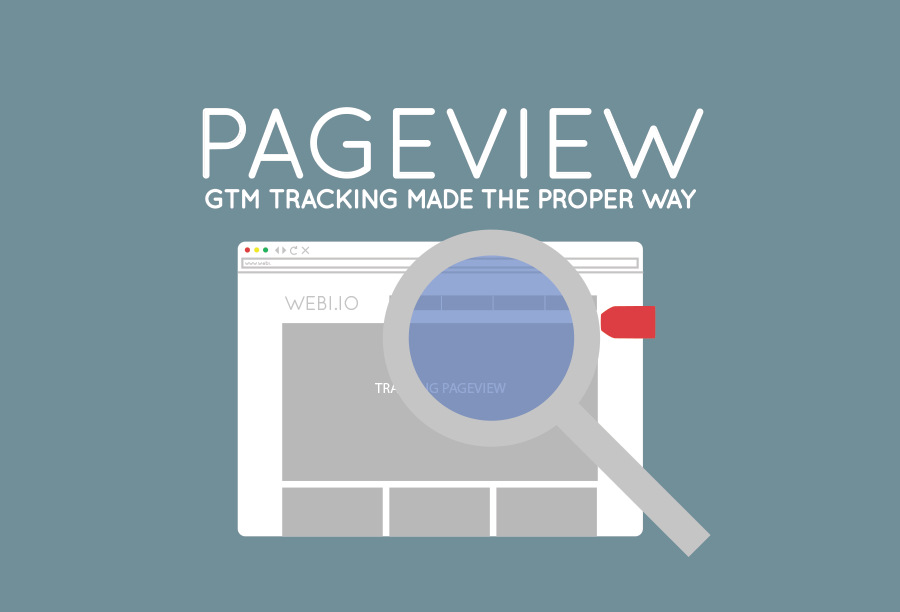Sebagai golongan yang masih memiliki pikiran yang waras, kita sering kali merasa jengah melihat berbagai hoax yang berseliweran di halaman utama media sosial kita. Entah bagaimana sebagian orang begitu mudahnya percaya dengan pelbagai berita yang tidak jelas asal usulnya.
Di era yang katanya disebut sebagai era Post-Turth ini, akan sangat sulit mencari kebenaran yang objektif Semuanya relatif dan amat subjektif, tergantung pada dari mana kita melihat (sudut pandang) dan juga siapa yang melihatnya. Hal ini akhirnya membuat batas antara suatu kebenaran dan kebohongan seakan begitu tipis.
Berawal dari Kebohongan menjadi Uang
Kebohongan yang pada sifat alamiah manusia itu menolaknya, namun saat itu sebagian orang justru memanfaatkannya sebagai ladang rezekinya Munculnya pelbagai isu yang simpang siur kebenarannya dan juga jutaan berita hoax adalah contohnya. Judul dalam berita-berita hoax didisain begitu “click bait”, yang mana membuat orang tertarik untuk mengkliknya. Salah satu tujuannya tentu saja page view. Blogger-blogger kecil yang mana dia belum mapan bisa dengan cepat mendapatkan pengunjung yang melimpah dengan cara seperti itu.
Mereka mengandalkan apa yang disebut ‘traffic‘–jumlah kunjungan ke suatu situs–untuk mendulang pundi-pundi materi dari blog atau halaman mereka. Bagi mereka yang ingin instan, memuat berita atau artikel dengan judul yang bombastis adalah salah satu pilihannya. Dan tentu saja akan dibumbui juga dengan rumor, kebohongan, informasi palsu, dan lain sebagainya.
Ryan Holiday dalam bukunya yang bertajuk “Trust Me, I’m Lying“, mengisahkan pergulatannya dengan dunia blogger (termasuk media elektroni/berita online). Dalam bukunya tersebut, Holiday menerangkan bahwa pendapatan terbesar para blogger dan pemilik media online ialah dari iklan, yang mana akan sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan ke situs atau blog tersebut. Maka sudah dipastikan bahwa setiap kali kita membuka sebuah situs, itu merupakan uang yang masuk ke kantong penerbitnya.
Ia (Holiday) juga menjelaskan bahwa dalam mekanisme iklan tersebut, seorang pembaca yang datang membaca dengan teliti tidak akan lebih baik dari mereka yang mengklik situs tersebut kemudian pergi. Begitupun terkait kontennya, sebuah artikel yang mengandung unsur nasihat yang bermanfaat, tidak lebih baik dari mereka yang menerbitkan konten berita atau artikel ‘sampah’. Selama halaman sudah tampil dan iklannya terlihat, maka kedua belah pihak sudah memenuhi tujuan mereka.
Berangkat dari hal itu, para penerbit melakukan segala upaya demi mengejar apa yang dikenal sebagai trafik. Maka di sinilah permasalahannya muncul, seorang penerbit kecil akan dihadapkan pada dua pilihan, yakni mau menerbitkan artikel atau berita yang standar tapi trafik web biasa atau cenderung rendah, atau menggunakan berita sampah seperti yang telah disebutkan sebelumnya supaya bisa menarik pengunjung lebih banyak dan akan berimbas lebih banyak pula uang yang masuk ke kantong penerbit.
Di titik itulah benturan antara pengejaran akan jumlah page view dengan sebuah moralitas. Bagi mereka yang cenderung mengesampingkan moralitas, maka akan melakukan berbagai cara demi mengejar trafik. Saat ini, yang mana dikenal dengan era Post-Turth mungkin golongan itulah yang lebih banyak. Golongan yang rela melakukan apa pun demi mengejar page view. Karena bagi mereka, semakin banyak page view, akan semakin banyak pula jumlah rupiah yang masuk.
Moralitas dalam Era Post-Turth
Dari penjabaran singkat tersebut akhirnya membawa kita kepada pertanyaan, “apakah moralitas masih ada dalam era Post-Turth?” Kita merasa risih mungkin dengan banyaknya berita-berita sampah dan hoax yang sekan tanpa henti menjejali media sosial kita. Namun hal itu merupakan konsekuensi dari hilangnya moralitas yang dimiliki oleh para blogger dan penerbit berita. Jika media dan blog didominasi oleh mereka yang sudah mengesampingkan moral, maka fenomena seperti ini akan semakin banyak. Tindakan yang tidak beretika tersebut didorong dari pengejaran akan sebuah materi tanpa mengenakan moralitas di tubuhnya.
Menjelang akhir tahun 2017 lalu, tepatnya pada bulan September, masyarakat muslim Indonesia khusus dan dunia pada umumnya dikejutkan dengan laporan dari Human Rights Watch (HRW) yang menunjukkan citra satelit sebuah perkampungan etnis Rohingya di Myanmar terbakar. Dipantik oleh gambar tersebut akhirnya isu pembantaian etnis Rohingya kembali mencuat ke permukaan. Pada dasarnya gambar yang dipublikasikan oleh HRW merupakan benar adanya. Namun dengan memanfaatkan isu Rohingya, ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan gambar palsu pembantaian etnis Rohingya.
Munculnya berbagai gambar palsu terkait pembantaian etnis tersebut justru membuat publik merasa skeptis akan kebenaran terjadinya pelbagai pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya. Meskipun sebenarnya benar-benar terjadi pembantaian di sana, namun foto-foto yang banyak beredar bukanlah asli yang dialami oleh etnis Rohingya dan disebabkan hal itulah yang membuat publik mendeskriditkan berita tentang pembantaian yang sesungguhnya.
Beredarnya foto-foto hoax tersebut juga semakin memicu umat Islam marah. Karenanya terjadi demonstrasi di beberapa negara muslim. Itu bagi mereka yang masih moderat, bagaimana dengan yang ekstrim? tidak menutup kemungkinan akan meledakan kedutaan besar Myanmar.
Contoh lebih dekat adalah sebagaimana yang terjadi di negeri kita. Pada 2017 lalu, seorang ayah yang mengirimkan nasi ke anak dihakimi massa karena mencurigainya sebagai penculik anak. Kala itu kabar palsu mengenai penculikan anak menyebar secara masif di Indonesia. Anda bisa melihatnya, betapa dahsyat efek dari sebuah hoax.
Post-Turth sendiri bagi penulis merupakan hasil dari hilangnya moralitas tadi. Mereka seakan sudah tidak peduli lagi dengan apa yang mereka publikasikan. Jubah-jubah moralitas mereka tanggalkan. Hanya jubah materi yang mereka kenakan. Demi sebuah page view, pembuat hoax rela menaggalkan moralitasnya.
Masihkah Ada Harapan?
Dalam situasi sesulit apa pun harapan akan tetap ada. Memang sudah sebuah konsekuensi jika perkembangan teknologi komunikasi tidak diimbangi dengan minat literasi. Publik akan terombang-ambing dalam suatu kebingungan sebab mereka tidak bisa membedakan mana informasi palsu dan mana yang asli. Hanya dengan literasilah hal tersebut bisa dihadapi. Artinya, mendorong masyarakat untuk menggali informasi secara dalam untuk kemudian memahaminya. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang secara masif menyebar informasi menyesatkan.
Yopi Makdori